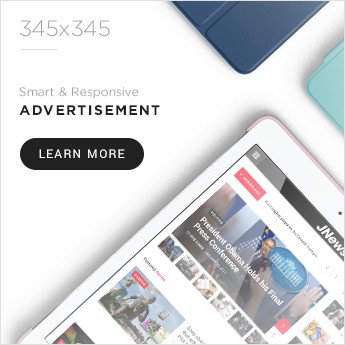Jakarta – Sebanyak 4.582 mahasiswa baru dari seluruh fakultas Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berkumpul secara virtual, Rabu (23/10), untuk mengikuti webinar Critical Thinking dalam rangkaian acara PROSPEKTIV 2025. Sesi ini dibawakan oleh pemateri Jaka Arya Pradana, founder dan CEO sebuah agentic AI startup.
Jakarta – Sebanyak 4.582 mahasiswa baru dari seluruh fakultas Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berkumpul secara virtual, Rabu (23/10), untuk mengikuti webinar Critical Thinking dalam rangkaian acara PROSPEKTIV 2025. Sesi ini dibawakan oleh pemateri Jaka Arya Pradana, founder dan CEO sebuah agentic AI startup.
Ketika AI Menjawab, Siapa yang Berpikir?
“Di era AI sekarang, kita sering bertanya pada AI
tanpa crosscheck kebenarannya. Padahal jawaban AI belum tentu akurat,”
ujar Jaka membuka sesi. Pernyataan sederhana itu langsung menyentuh realitas
mahasiswa yang tumbuh di era ChatGPT.
Ia kemudian memberikan contoh mengejutkan: sebuah
penelitian MIT Media Lab yang viral dengan headline media “Menggunakan
ChatGPT bikin lebih bodoh.” Sebagai critical thinker, Jaka mengajak
mahasiswa untuk tidak langsung percaya. “Kita perlu cek: seperti apa
metode penelitiannya? Apa yang dimaksud ‘lebih bodoh’?”
Ternyata, penelitian oleh Dr. Nataliya Kosmyna berjudul
“Your Brain on ChatGPT” melibatkan 54 mahasiswa yang dibagi tiga
kelompok: menulis esai dengan otak saja, dengan Google, dan dengan ChatGPT.
Kelompok ChatGPT menunjukkan aktivitas otak paling lemah.
“Tapi ini bukan berarti ChatGPT membuat bodoh. Ini
berarti penggunaan AI tanpa critical thinking membuat otak kita pasif,”
jelas pria yang memiliki lebih dari 13 tahun pengalaman mengembangkan sistem AI
berskala enterprise ini. “Yang penting bukan menghindari AI, tapi
menggunakan AI dengan bijak.”
Membedah Argumen yang Terdengar Meyakinkan
Jaka mengajak mahasiswa bermain detektif logika. Argumen
pertama: “Lulusan universitas ternama pasti sukses. Jadi kalau mau sukses,
harus masuk universitas ternama.”
Melalui polling, mayoritas mahasiswa menganggap argumen
itu cacat. Intuisi mereka ternyata tepat. Setelah dibedah menggunakan
Paul-Elder Critical Thinking Framework, terungkap logical fallacy
“Correlation ≠ Causation”. “Memang benar banyak lulusan
universitas ternama yang sukses. Tapi apakah karena mereka dari universitas
ternama? Atau karena faktor lain seperti kerja keras, networking, atau
skill?”
Argumen kedua lebih menohok: “Tidak perlu belajar
matematika karena ada AI dan kalkulator.” Setelah dianalisis, terungkap
argumen ini mengandung asumsi tersembunyi dan logical fallacy “False
Dilemma”. “Matematika bukan cuma tentang hitung-hitungan. Matematika
melatih cara berpikir untuk solve complex problems dan analyze patterns,”
terang mantan AVP AI Product Management di Indosat ini.
Pertanyaan yang Menyentuh Inti
Di tengah sesi, seorang mahasiswa UPN Veteran Jakarta bertanya:
“Banyak orang percaya berpikir kritis artinya menentang atau mengkritisi
berlebihan. Bagaimana menyeimbangkannya?”
Jaka menjawab, “Inti dari berpikir kritis adalah
berpikir jernih dan rasional. Dalam argumen bisa jadi tidak semuanya salah –
bisa jadi ada yang benar, bahkan solid. Jika argumennya solid, harus kita
terima. Bila ada yang benar, apresiasi dulu baru kritisi dengan santun dan
elegan. Terkadang problemnya bukan pada isinya, tapi cara
menyampaikannya.”
Pertanyaan kedua dari seorang mahasiswi UPN Veteran
Jakarta, “Mengapa kemampuan berpikir kritis lebih penting daripada
pelajaran mata kuliah?”
Mantan Lead Data Scientist di Telkom ini merespons dengan
perspektif praktis: “Keduanya penting. Di awal-awal saya bekerja,
pelajaran kuliah sangat terpakai. Tapi berpikir kritis juga penting karena kita
harus membuat argumen yang jernih dan rasional agar diterima stakeholder,
seperti atasan, rekan kerja, partner, maupun klien. Critical thinking juga
memperkuat kemampuan problem solving untuk menyelesaikan berbagai tantangan di
dunia kerja.”
Dari Startup AI ke Ruang Kelas Virtual
Deangan latar belakangnya yang telah membantu puluhan perusahaan
mengimplementasikan AI dari nol sampai implementasi dan operasional, Jaka
memberikan perspektif unik kepada para mahasiswa. Pria yang dapat dihubungi melalui LinkedIn
ini tidak hanya berbicara dari teori, tetapi dari pengalaman langsung membangun
dan mengimplementasikan solusi AI.
“Yang terpenting bagaimana manusia menggunakannya
dengan bijak. Di dunia kerja, AI bisa kasih data, tapi kalian yang harus
evaluate: apakah data ini akurat? Apakah kesimpulan ini logis? Apakah ada
perspektif lain?”
Meski dihadiri ribuan peserta, Jaka yang juga Jakarta City
Lead di Buildclub.ai, komunitas para AI builder di seluruh dunia ini, berhasil
menciptakan suasana interaktif. Ia juga membahas berbagai jenis cognitive bias dan logical fallacy dalam webinar
tersebut.
Kebebasan untuk Berpikir
Di penghujung sesi, Jaka meninggalkan pesan resonan,
“Critical thinking bukan tentang jadi orang yang skeptis terhadap
segalanya atau selalu debat. Critical thinking adalah tentang kebebasan. Ketika
kalian bisa berpikir kritis, kalian tidak lagi menjadi budak dari opini orang
lain, manipulasi media, tekanan sosial, informasi yang salah, dan keputusan
yang buruk.”
Ia menutup dengan tiga tantangan, yaitu selalu bertanya,
selalu verifikasi, dan selalu refleksi.
Antusiasme yang terlihat dari aktifnya chat, polling, dan
diskusi menunjukkan bahwa critical thinking bukan sekadar topik akademis. Di
era AI yang dipenuhi informasi dari berbagai sumber, kemampuan untuk berpikir
jernih dan rasional menjadi semakin krusial.
Ketika webinar berakhir, ribuan mahasiswa UPN Veteran
Jakarta itu tidak hanya membawa pengetahuan tentang Critical Thinking Framework,
Cognitive Bias dan Logical Fallacies. Mereka membawa kesadaran
bahwa pikiran mereka adalah milik mereka sendiri, dan mereka punya kuasa untuk
memilih bagaimana menggunakannya.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES